Bank Dunia bilang daya beli RI lemah karena upah rendah. Di sisi lain, AI perbankan tumbuh cepat. Bagaimana AI bisa benar-benar bantu pekerja bergaji kecil?
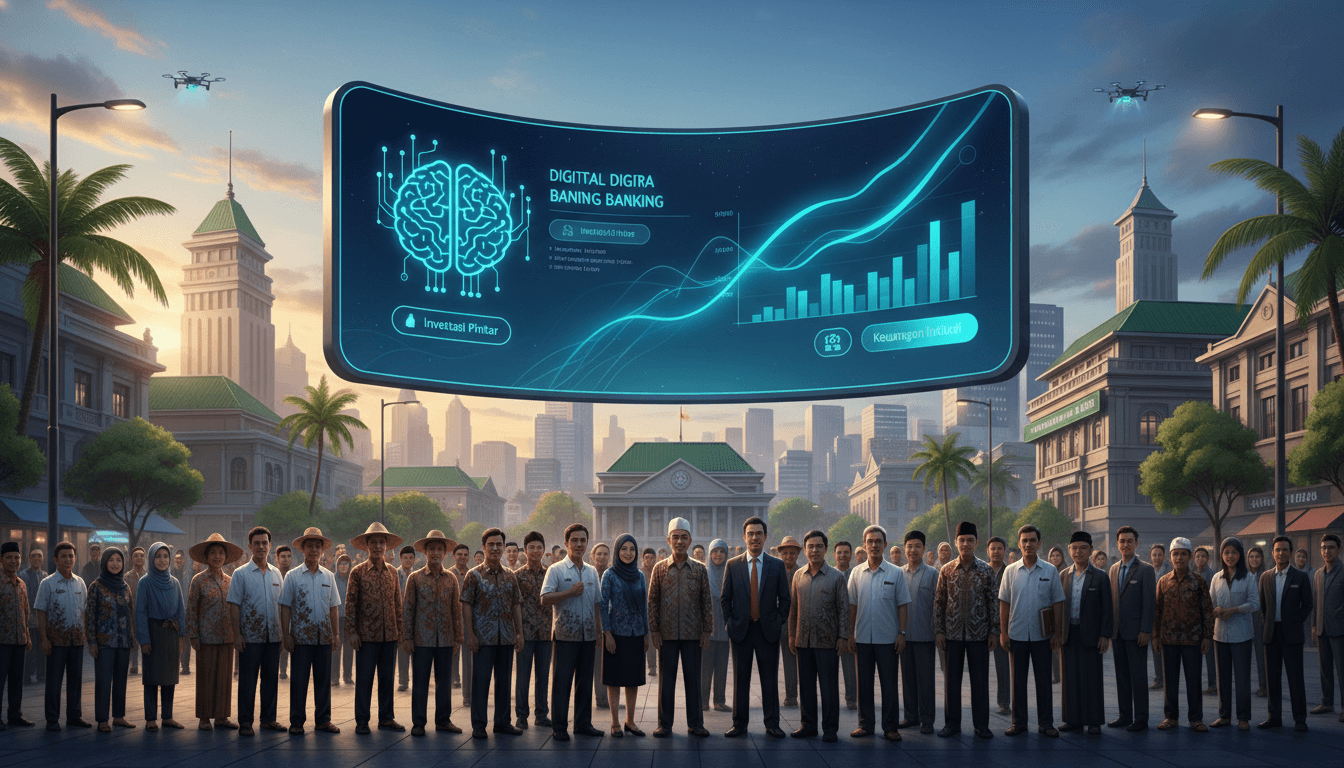
Upah Rendah, Daya Beli Lemah: Saatnya AI Perbankan Turun Tangan
Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di kisaran 5%, tapi Bank Dunia mencatat upah riil turun rata-rata 1,1% per tahun sejak 2018. Artinya sederhana: angka PDB membaik, tapi dompet banyak orang tetap terasa “tipis”.
Ini bukan sekadar statistik. Ini realitas pekerja yang gajinya stagnan, UMKM yang susah dapat kredit, dan keluarga yang makin hati-hati belanja menjelang akhir tahun seperti sekarang, Desember 2025.
Di tengah kondisi ini, perbankan Indonesia sedang masuk fase baru: era digital banking berbasis AI. Kalau hanya dipakai untuk bikin aplikasi makin keren, kita rugi besar. AI di perbankan punya potensi jauh lebih penting: membantu menjawab masalah daya beli lemah dan upah rendah lewat inklusi keuangan yang lebih adil dan tepat sasaran.
Artikel ini membedah temuan Bank Dunia soal daya beli, lalu menghubungkannya dengan satu pertanyaan praktis: bagaimana AI di perbankan Indonesia bisa benar-benar membantu masyarakat berpenghasilan rendah, bukan cuma nasabah mapan di kota besar?
Apa Sebenarnya yang Dibilang Bank Dunia Soal Daya Beli RI?
Intinya, Bank Dunia melihat konsumsi rumah tangga Indonesia terancam stagnan hingga 2027 karena dua hal utama:
- Banyak pekerja masuk sektor bergaji rendah (terutama pertanian, akomodasi, makanan-minuman)
- Upah riil turun terus sejak 2018, terutama untuk pekerja berkeahlian menengah dan tinggi
Beberapa angka penting dari laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) Desember 2025:
- Pertumbuhan konsumsi rumah tangga 2025–2027 diproyeksi hanya sekitar 4,9%, lebih rendah dari 5% di 2022 dan 5,1% di 2024.
- Tambahan lapangan kerja Agustus 2024 – Agustus 2025 hanya sekitar 1,9 juta (1,3% yoy), turun dari 4,8 juta tahun sebelumnya.
- Mayoritas pekerjaan baru ada di pertanian (+0,49 juta) dan akomodasi & makanan-minuman (+0,42 juta) dengan rata-rata upah sekitar Rp2,55 juta/bulan, di bawah rata-rata nasional Rp3,33 juta/bulan.
- Upah riil 2018–2024:
- Turun rata-rata 1,1% per tahun secara keseluruhan.
- Turun 2,3% per tahun untuk pekerja berkeahlian tinggi.
- Turun 1,1% per tahun untuk keahlian menengah.
- Naik tipis 0,3% per tahun untuk keahlian rendah.
Dari sisi komposisi tenaga kerja:
- Porsi pekerja berkeahlian menengah turun dari 71,1% (2018) ke 68,3% (2024).
- Porsi pekerja berkeahlian rendah justru naik 2,3 poin persentase.
- Pekerja berkeahlian tinggi naik, tapi sangat terbatas.
Masalah makin berat kalau bicara perempuan muda:
- Usia sekitar 19 tahun: 16,6% perempuan muda NEET, dua kali lipat laki-laki (7,9%).
- Usia sekitar 24 tahun: perempuan 39,2% NEET, laki-laki hanya 3,8%.
- Usia produktif 25–54 tahun: ketidakaktifan perempuan 36,2%, jauh di atas rata-rata negara berpendapatan menengah atas (29%) dan tinggi (19,7%).
Carolyn Turk, Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, merangkumnya begini:
“Meningkatkan kapasitas perekonomian dan memungkinkan sektor swasta menciptakan lapangan kerja dengan upah yang lebih baik bagi generasi muda Indonesia menjadi tujuan utama saat ini.”
Masalahnya: sektor swasta, termasuk bank, sering masih bermain aman. Kredit mengalir ke yang sudah bankable, layanan terbaik hanya dirasakan segmen menengah atas. Di sinilah AI dalam perbankan sebenarnya bisa mengubah pola.
Mengapa Upah Rendah dan Daya Beli Lemah Harus Jadi Isu Bank dan Fintech
Banyak orang melihat isu upah sebagai urusan pemerintah dan dunia usaha. Padahal, perbankan dan fintech memegang satu kunci penting: akses keuangan yang adil.
Upah rendah dan konsumsi lemah langsung berkaitan dengan hal-hal ini:
- Sulit menabung, sehingga masyarakat rentan terhadap guncangan (PHK, sakit, biaya pendidikan).
- Sulit mengakses kredit produktif, terutama bagi pekerja informal dan berpenghasilan rendah.
- UMKM sulit naik kelas, karena rasio pinjaman ke kelompok rentan masih rendah.
Kalau sistem perbankan hanya mengandalkan metode lama—skor kredit tradisional, slip gaji formal, riwayat pinjaman di bank—maka jutaan orang dengan potensi produktif akan terus berada di luar sistem. Daya beli tidak akan bergerak banyak.
Di sinilah AI dan data alternatif jadi relevan.
- Pekerja informal yang tidak punya slip gaji, sebenarnya punya jejak transaksi digital: e-commerce, dompet digital, pembayaran listrik, pulsa, transportasi online.
- Pelaku UMKM punya data omzet harian dari aplikasi POS, marketplace, atau payment gateway.
Tanpa AI, data ini terlalu besar dan rumit untuk dianalisis manual. Dengan AI, bank bisa memetakan risiko dan kemampuan bayar dengan jauh lebih akurat, bahkan untuk orang yang belum pernah menyentuh produk perbankan formal.
Peran Konkret AI Perbankan untuk Masyarakat Berupah Rendah
AI dalam industri perbankan Indonesia bukan lagi sekadar konsep. Beberapa peran konkret sudah mulai terlihat, dan kalau digarap serius, bisa nyambung langsung dengan masalah yang disorot Bank Dunia.
1. Penilaian Kredit Alternatif untuk Pekerja Bergaji Rendah
Ini titik paling krusial.
Masalah lama:
- Buruh harian, pekerja informal, ojek online, penjaga warung, pekerja restoran kecil—banyak yang tidak punya slip gaji resmi.
- Bank sulit menilai profil risiko hanya dari data tradisional.
- Akibatnya, mereka lari ke pinjol ilegal atau rentenir dengan bunga tinggi.
Solusi AI:
AI bisa memproses data alternatif seperti:
- Pola pemasukan dan pengeluaran dari rekening atau e-wallet.
- Riwayat pembayaran tagihan (listrik, air, internet, cicilan HP).
- Aktivitas transaksi di e-commerce dan aplikasi transportasi.
- Data usaha dari aplikasi kasir digital atau marketplace.
Dari situ, AI membangun skor kredit alternatif yang lebih adil:
- Orang yang gajinya kecil tapi disiplin bayar tagihan bisa dinilai layak.
- UMKM dengan omzet stabil, meski tanpa laporan keuangan formal, bisa mendapatkan limit kredit.
Kalau hal ini diterapkan luas, pekerja di sektor dengan rata-rata upah Rp2,55 juta seperti pertanian dan F&B bukan lagi otomatis “tidak bankable”. Mereka bisa mengakses:
- Kredit produktif skala kecil.
- Tabungan berjangka mikro.
- Asuransi dasar dengan premi terjangkau.
2. Personalisasi Produk Keuangan untuk Segmen Rentan
Selama ini, banyak produk bank didesain top-down: satu jenis rekening, satu paket biaya, satu jenis kartu, ditawarkan ke semua segmen.
AI memungkinkan segmentasi yang jauh lebih detail:
- Pekerja paruh waktu di kota kecil dengan penghasilan di bawah Rp3 juta/bulan.
- Perempuan usia 24–35 tahun yang tidak aktif bekerja tapi aktif mengelola keuangan rumah tangga.
- Petani dengan pola pendapatan musiman.
Dengan pola seperti ini, bank digital bisa merancang produk yang lebih nyambung dengan realitas:
- Rekening tanpa biaya admin, dengan fitur “celengan digital” otomatis dari sisa saldo.
- Cicilan mikro dengan tenor fleksibel mengikuti pola pendapatan (misal musiman untuk petani).
- Limit pinjaman yang bertahap naik turun berdasarkan perilaku transaksi, bukan hanya gaji.
Buat masyarakat berupah rendah, personalisasi seperti ini jauh lebih relevan dibanding produk “serba generik” yang sering terasa mahal dan rumit.
3. Chatbot Bahasa Indonesia yang Benar-Benar Membantu, Bukan Bikin Emosi
Bagi segmen berpenghasilan rendah dan generasi yang kurang akrab dengan istilah keuangan, edukasi adalah separuh pertempuran.
AI chatbot yang:
- Bisa berbahasa Indonesia non-formal,
- Mengerti istilah sehari-hari (“cicilan macet”, “rekening ke-block”, “tabungan terkuras”),
- Tersedia 24 jam di aplikasi ringan,
bisa menjadi frontline edukasi keuangan yang murah dan efektif.
Contoh peran nyata chatbot AI:
- Menjelaskan risiko pinjaman berbunga tinggi dengan bahasa sederhana.
- Memberi simulasi: “Kalau kamu pinjam Rp2 juta, dengan bunga sekian dan tenor sekian, cicilan per bulan segini.”
- Mengingatkan jatuh tempo tagihan agar orang tidak mudah terjebak denda.
Kalau dirancang dengan empati, chatbot tidak hanya mengurangi beban call center, tapi juga membantu orang mengelola gaji yang pas-pasan dengan lebih cerdas.
4. Deteksi Fraud untuk Melindungi Nasabah Rentan
Kita tahu, nasabah yang paling sering tertipu phishing, social engineering, dan penipuan online justru sering berasal dari kelompok berpendapatan menengah bawah.
AI di perbankan bisa:
- Mendeteksi pola transaksi mencurigakan dalam hitungan detik.
- Mengirim notifikasi real-time: “Transaksi tidak biasa terdeteksi, apakah ini Anda?”
- Memblokir sementara transaksi sampai ada konfirmasi.
Bagi nasabah dengan saldo terbatas, kehilangan Rp1–2 juta bisa berarti hilangnya uang belanja satu bulan penuh. Perlindungan berbasis AI ini nyambung langsung ke isu daya beli yang digarisbawahi Bank Dunia.
Dimensi Gender: Bagaimana AI Bisa Lebih Pro-Perempuan
Data Bank Dunia soal perempuan muda yang NEET harusnya jadi alarm besar. Upah rendah dan ketidakaktifan perempuan di pasar kerja bukan hanya isu sosial, tapi juga isu finansial.
Perempuan yang tidak punya akses keuangan formal cenderung:
- Lebih sulit membangun usaha rumahan (catering, jahit, reseller, dan lain-lain).
- Bergantung pada penghasilan pasangan, sehingga rentan jika terjadi perceraian, PHK, atau musibah.
AI di perbankan bisa diarahkan untuk lebih pro-perempuan, misalnya:
- Model skor kredit yang mengakui aktivitas ekonomi informal perempuan, seperti transaksi grosir, arisan digital, penjualan online.
- Penawaran produk modal kerja mikro yang dikirimkan proaktif ke perempuan yang aktif bertransaksi jual-beli online, meski tidak terdaftar sebagai pelaku UMKM formal.
- Chatbot dan modul edukasi keuangan yang menargetkan perempuan usia 19–35 tahun, membahas cara mengelola keuangan rumah tangga, memulai usaha kecil, dan mengatur cicilan.
Kalau dimanfaatkan baik, AI justru bisa mengurangi bias lama di perbankan yang cenderung melihat perempuan—apalagi yang tidak bekerja formal—sebagai nasabah kelas dua.
Tantangan: AI Bisa Membantu, Tapi Harus Disetir dengan Benar
Saya cukup optimistis dengan peran AI di perbankan, tapi ada beberapa risiko yang harus diakui jujur.
-
Bias data
- Kalau data historis lebih banyak merekam nasabah mapan di kota besar, model AI cenderung “meniru” bias itu.
- Hasilnya, segmen berpenghasilan rendah tetap saja sulit disetujui, hanya dengan cara yang lebih canggih.
-
Transparansi keputusan kredit
- Nasabah perlu penjelasan sederhana: kenapa pengajuan kredit ditolak, apa yang bisa diperbaiki.
- Kalau AI dianggap “kotak hitam”, kepercayaan publik akan turun.
-
Literasi digital
- Tidak semua pekerja berupah rendah nyaman dengan aplikasi yang rumit.
- Desain UI/UX dan edukasi harus disesuaikan dengan realitas mereka.
Artinya, AI bukan obat mujarab otomatis. AI hanya sekuat niat dan desain kebijakan di belakangnya. Kalau tujuan bisnis bank hanya mengejar margin dari segmen paling aman, AI akan mempercepat eksklusi, bukan inklusi.
Justru di sini bedanya institusi keuangan yang serius membangun masa depan Indonesia, dengan yang hanya ikut tren digital banking.
Langkah Praktis: Apa yang Bisa Dilakukan Bank, Fintech, dan Regulator?
Agar AI benar-benar membantu menjawab masalah yang diangkat Bank Dunia, beberapa langkah konkret menurut saya cukup realistis:
-
Bank & fintech:
- Bangun model skor kredit alternatif yang eksplisit menargetkan pekerja informal, petani, dan pekerja sektor bergaji rendah.
- Uji coba produk kredit mikro dengan limit kecil dan monitoring ketat, sambil belajar dari data perilaku bayar.
- Investasi serius di chatbot bahasa Indonesia (dan bahasa daerah utama) yang fokus pada edukasi keuangan.
-
Regulator:
- Menyusun aturan pemakaian data alternatif yang melindungi privasi nasabah tapi tetap memungkinkan inovasi.
- Mendorong sandbox regulasi untuk model penilaian kredit berbasis AI yang menyasar inklusi keuangan.
-
Kolaborasi lintas sektor:
- Integrasi data dengan platform e-commerce, transportasi online, dan payment gateway untuk membangun profil risiko yang lebih kaya.
- Program khusus perempuan dan generasi muda dengan kombinasi pelatihan literasi keuangan + akses produk keuangan berbasis AI.
Kalau tiga sisi ini bergerak bareng, kita tidak hanya bicara teori “AI dalam industri perbankan Indonesia”, tapi dampak nyata di lapangan:
- Pekerja di sektor bergaji rendah punya jalan keluar dari lingkaran rentenir dan pinjol ilegal.
- UMKM yang selama ini “tak terlihat” oleh bank menjadi bisa diukur dan dibiayai.
- Perempuan yang tadinya hanya jadi pengelola uang belanja, bisa naik kelas menjadi pelaku ekonomi yang diakui sistem perbankan.
Penutup: Dari Statistik Bank Dunia ke Solusi Nyata lewat AI
Laporan Bank Dunia soal daya beli lemah dan upah rendah bukan sekadar bahan diskusi ekonom. Itu cermin bahwa jutaan orang Indonesia bekerja keras, tapi masih jauh dari aman secara finansial.
Di saat yang sama, kita sedang berada di titik penting transformasi digital banking berbasis AI. Kalau AI hanya dipakai untuk mempercepat transaksi dan memperindah aplikasi, kita sedang menyia-nyiakan momentum.
AI dalam perbankan Indonesia punya peran strategis:
- Membuat penilaian kredit lebih adil bagi pekerja berpenghasilan rendah.
- Mendorong inklusi keuangan yang menyasar perempuan dan generasi muda yang selama ini tertinggal.
- Membantu masyarakat mengelola gaji yang pas-pasan dengan lebih terencana dan aman.
Ke depan, bank dan fintech yang paling dipercaya publik bukan yang paling ramai iklannya, tapi yang paling terasa manfaatnya di level dompet sehari-hari. Di situlah AI seharusnya bekerja: senyap di belakang layar, tapi nyata mengurangi kerentanan finansial jutaan orang.